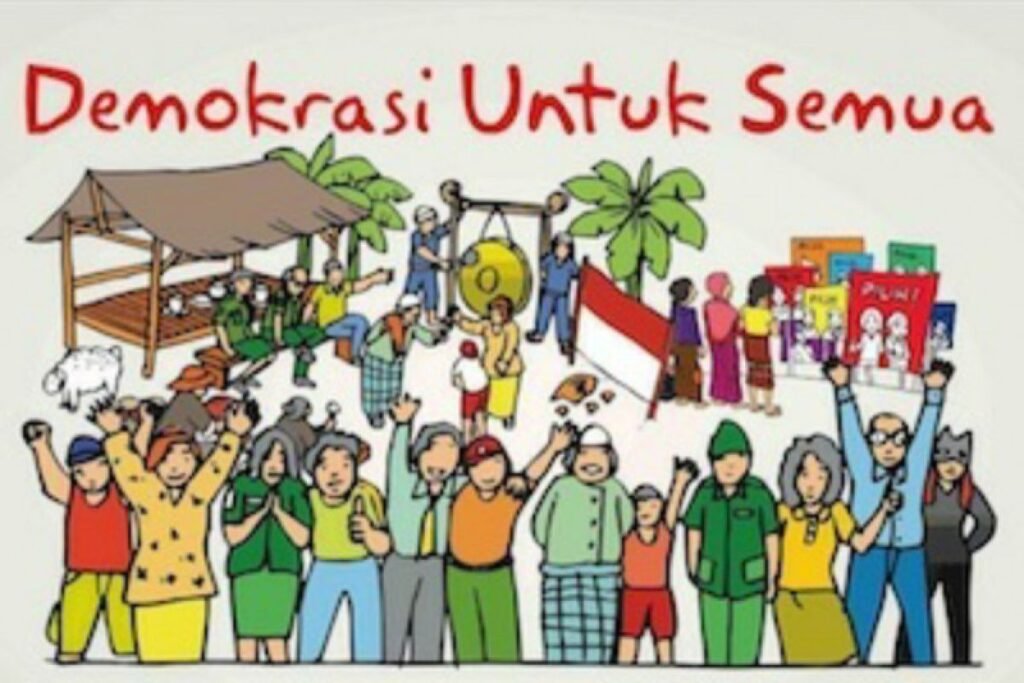Oleh : Ahmad Tholabi Kharlie Dosen Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
PRADANAMEDIA / Demokrasi Indonesia kini berada di titik kritis. Dua puluh lima tahun setelah reformasi, sistem demokrasi memang tampak berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan arah moral dan visi kebangsaan. Pemilu tetap terselenggara dengan tertib, namun hasilnya kerap menjauh dari cita-cita konstitusi.
Revisi Undang-Undang Pemilu yang tengah dibahas di parlemen menjadi momentum penting untuk menata ulang fondasi demokrasi elektoral Indonesia. Bukan sekadar menyempurnakan teknis pemungutan suara, melainkan mengembalikan hukum pemilu sebagai instrumen peradaban politik yang bermartabat dan berkeadilan.
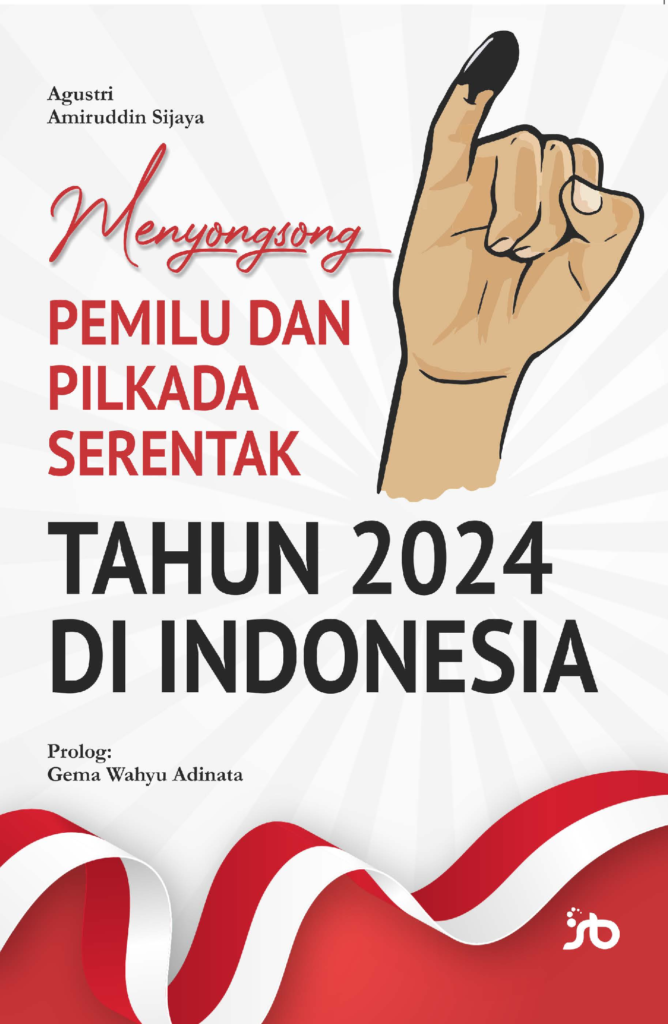
Seperti diingatkan Jimly Asshiddiqie (2022), demokrasi Indonesia kini berjalan rutin, tetapi kehilangan kualitas substantifnya. Demokrasi telah direduksi menjadi seremonial lima tahunan tanpa makna etik. Pandangan serupa diutarakan Larry Diamond (2019), yang menyebut fenomena ini sebagai electoral fatigue — kelelahan demokrasi akibat pemilu yang gagal membawa perubahan nyata.
Pertanyaan mendasarnya: untuk siapa pemilu diselenggarakan? Untuk rakyat sebagai pemilik kedaulatan, atau untuk elite sebagai pemegang kekuasaan formal? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah revisi UU Pemilu ke depan.
Kodifikasi: Jalan Tengah untuk Menata Ulang Sistem
Perdebatan awal revisi UU Pemilu bermula dari pendekatan yang akan digunakan: kodifikasi atau omnibus law. Model omnibus dinilai efisien karena menyatukan berbagai aturan dalam satu payung hukum besar. Namun, secara realistis, sistem politik dan kelembagaan Indonesia belum cukup siap menerapkannya pada hukum pemilu yang kompleks dan multiaktor.
Pilihan paling rasional adalah model kodifikasi, yakni penyatuan seluruh norma pemilu nasional dan lokal dalam satu kitab hukum pemilu Indonesia. Pendekatan ini akan memperkuat konsistensi, kepastian, dan kesatuan arah sistem elektoral.
Giovanni Sartori (1997) menekankan pentingnya institutional coherence atau koherensi institusional sebagai syarat keberhasilan demokrasi. Tanpa keseragaman sistem hukum, demokrasi tumbuh timpang dan tidak stabil. Sementara Arend Lijphart (2012) mengingatkan, desain pemilu yang sederhana dan stabil menjadi fondasi sistem politik yang sehat.
Kodifikasi bukan langkah revolusioner, tetapi reformasi struktural yang progresif. Ia akan melahirkan satu kesatuan hukum pemilu yang utuh, transparan, dan menjamin keadilan representatif bagi seluruh warga negara.
Sistem Terbuka Terbatas: Keseimbangan antara Rakyat dan Partai
Salah satu isu klasik yang kembali mencuat adalah pilihan antara sistem proporsional terbuka atau tertutup. Sistem terbuka memberi rakyat hak memilih langsung calon legislatif, tetapi di lapangan justru memicu persaingan brutal antar-kader, biaya politik tinggi, dan praktik politik uang.
Sebaliknya, sistem tertutup memang memperkuat peran partai, tetapi mengurangi kontrol rakyat terhadap wakilnya. Karena itu, model proporsional terbuka terbatas (semi-terbuka) bisa menjadi jalan tengah.
Dalam sistem ini, rakyat tetap memilih calon, namun daftar calon ditentukan melalui seleksi internal partai yang transparan dan meritokratis. Konsep ini sejalan dengan pandangan Pippa Norris (2014) dalam Why Elections Fail, bahwa sistem pemilu yang ideal harus menyeimbangkan partisipasi rakyat dengan tanggung jawab partai politik.
Demokrasi sejati, tulis Robert A. Dahl (1989), bukan diukur dari seberapa sering rakyat memilih, tetapi sejauh mana mereka mampu mengontrol kekuasaan.
Setelah Presidential Threshold Dihapus: Mendesain Ulang Kompetisi
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus presidential threshold menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi konstitusional Indonesia. Ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional selama dua dekade telah menutup ruang kompetisi yang adil.
Kini, setiap partai yang memenuhi syarat administratif berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tantangan berikutnya adalah bagaimana mendesain ulang mekanisme pencalonan agar tidak menimbulkan ledakan kandidat tanpa arah politik yang jelas.
Fareed Zakaria (2003) mengingatkan bahwa kebebasan politik tanpa tanggung jawab kelembagaan hanya akan melahirkan populisme dan instabilitas. Karena itu, revisi UU Pemilu harus memastikan proses verifikasi calon yang ketat dan transparan, agar hanya pemimpin berintegritas dan berkapasitas yang dapat tampil di panggung politik nasional.
Menurunkan Ambang Batas Parlemen, Mengembalikan Nilai Suara Rakyat
Isu lain yang tak kalah penting adalah parliamentary threshold sebesar 4 persen. Meskipun dimaksudkan untuk mencegah fragmentasi, ambang batas ini justru menimbulkan paradoks: lebih dari 17 juta suara rakyat hangus dalam Pemilu 2024 karena partai yang mereka pilih tidak lolos.
Fenomena ini bertentangan dengan asas proporsionalitas — one person, one vote, one value.
Arend Lijphart (1999) memperingatkan, ambang batas yang terlalu tinggi justru merusak representasi minoritas dan memudarkan keadilan politik. Karena itu, revisi UU Pemilu sebaiknya menurunkan threshold menjadi 2,5–3 persen, dan bahkan menghapusnya untuk level DPRD.
Tujuannya bukan memberi ruang bagi partai kecil semata, melainkan mengembalikan kedaulatan suara rakyat sebagai dasar legitimasi demokrasi.
Politik Uang: Ancaman Terbesar bagi Demokrasi
Tak ada isu yang lebih berbahaya bagi demokrasi selain politik uang. Fenomena vote buying kini bukan lagi pelanggaran individual, tetapi strategi sistemik yang menukar suara rakyat dengan uang tunai.
Pippa Norris (2018) menyebut ini sebagai the dark side of electoral integrity — sisi gelap demokrasi yang mengubah kewargaan menjadi komoditas. Larry Diamond (2019) menegaskan, politik uang adalah penyebab utama kemunduran demokrasi di negara berkembang.
Untuk itu, revisi UU Pemilu harus memutus mata rantai uang dalam politik.
Pertama, dengan memperkuat kewenangan Bawaslu melalui sistem penegakan cepat (quick adjudication system).
Kedua, mewajibkan transparansi dana kampanye berbasis digital.
Ketiga, mendorong pendidikan politik berkelanjutan oleh partai-partai, agar pemilih rasional tumbuh dari kesadaran, bukan dari transaksi.
Hukum Pemilu sebagai Kontrak Moral Bangsa
Revisi UU Pemilu tidak boleh dipandang semata sebagai pekerjaan legislatif. Ia adalah ikhtiar membangun peradaban politik baru.
Saldi Isra (2021) mengingatkan, demokrasi hanya bermakna bila hukum dirancang untuk mengontrol kekuasaan, bukan melayaninya.
Sejalan dengan Robert Dahl (2000), demokrasi sejati harus menjamin bahwa suara setiap warga negara memiliki nilai yang sama, tidak dikalahkan oleh uang atau dominasi elite.
Karena itu, hukum pemilu ke depan harus berfungsi untuk:
- Menjaga kedaulatan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan.
- Menjamin keadilan representatif dan proporsionalitas politik.
- Menumbuhkan akuntabilitas moral dan integritas kepemimpinan.
Hukum pemilu adalah kontrak moral antara negara dan rakyatnya. Di dalamnya terkandung cita-cita agar kekuasaan tunduk pada etika dan rakyat ditempatkan sebagai subjek utama demokrasi.
Jika revisi kali ini gagal menyeimbangkan antara stabilitas dan keadilan, maka demokrasi kita akan terus tersandera oleh oligarki dan politik uang. Sebaliknya, bila dilandasi nalar konstitusional dan keberanian moral, UU Pemilu baru bisa menjadi tonggak demokrasi yang rasional, adil, dan bermartabat. (RH)