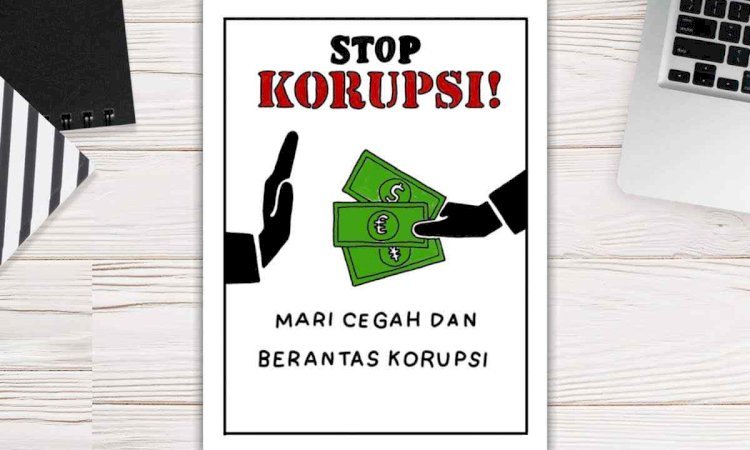Di banyak forum kebijakan publik, saya sering mengangkat argumen bahwa saat ini pemerintahan daerah (Pemda) kita mengalami fenomena “prematur” — baik dari sisi otonomi maupun kemandirian fiskal. Banyak Pemda masih sangat bergantung pada pemerintah pusat, baik dalam hal anggaran maupun arah kebijakan. Bahkan ketika ingin membuat terobosan, sering muncul ketakutan berlebih jika langkah mereka tak sejalan dengan arahan pusat.
Ini belum berbicara soal kemampuan teknokratis kepala daerah, kompetensi pejabat, hingga faktor politik seperti pengaruh warna partai terhadap hubungan pusat-daerah. Seperti dikatakan Prof. Djohermansyah Djohan, otonomi daerah kini semakin merana dan tersentralisasi, diperparah dengan perilaku koruptif mayoritas aktor lokal, senin, (28/4)

Fenomena ini semakin disorot saat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima 341 usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) hingga April 2025, mencakup pembentukan provinsi, kabupaten, kota, serta daerah istimewa dan khusus. Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik memaparkan rincian usulan ini dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada 24 April 2025.
Tentu, setiap daerah berhak mengusulkan pemekaran. Namun, tanpa strategi besar (grand design) dari pusat, kita hanya akan mengulang masalah lama: pemekaran berbasis kepentingan politik, tanpa evaluasi objektif berbasis kebutuhan rakyat dan kapasitas fiskal. Kita harus jujur bertanya:
- Bagaimana mungkin Pemda yang belum mandiri fiskal justru dimekarkan?
- Bagaimana mungkin saat korupsi daerah begitu menggurita, pemekaran wilayah masih dijadikan agenda?
- Mengapa tidak fokus memperkuat kemandirian dan profesionalisme Pemda yang ada?
Realitas di lapangan menunjukkan: setelah pemekaran, banyak Pemda “mekar tapi tidak kekar”. Pemerintahan Prabowo Subianto harus berani bersikap tegas seperti masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sempat menolak pemekaran tidak bermanfaat.
Belajar dari Otonomi Khusus Papua, meski alokasi anggaran pendidikan 30% diatur dalam UU No. 2/2021, realisasi di banyak daerah Papua bahkan belum memenuhi 20% mandatory spending. Ini menunjukkan lemahnya komitmen daerah terhadap sektor prioritas, dan lemahnya tata kelola keuangan daerah.
Kasus serupa terjadi di Aceh, di mana pembangunan RS Regional Langsa yang dibiayai dana Otonomi Khusus (Otsus) mandek sejak 2018 karena perubahan prioritas anggaran. Ini memperlihatkan betapa rentannya proyek strategis mangkrak karena lemahnya perencanaan fiskal dan teknokratisme.
Fenomena “mekar tapi tak kekar” ditegaskan oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid (2009) bahwa daerah hasil pemekaran sering menjadi beban baru tanpa progres berarti, melainkan justru membengkakkan biaya operasional. Data Kementerian Keuangan menunjukkan, Dana Alokasi Umum (DAU) melonjak dari Rp 54,31 triliun pada 1999 menjadi Rp 446 triliun pada 2025, namun tak sebanding dengan kualitas layanan publik.
Di banyak daerah baru, alokasi belanja modal dan pegawai menyedot hampir seluruh APBD, meninggalkan sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dalam kondisi mengenaskan. Alih-alih memperpendek jarak layanan publik, pemekaran memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat.
Lebih buruk lagi, pemekaran membuka ruang politisasi lokal: jabatan, dinas baru, dan DPRD baru menjadi ladang rebutan elite lokal. Rakyat, yang seharusnya menjadi pusat perhatian, justru dijadikan komoditas elektoral. Proses demokrasi makin mahal, korupsi politik meningkat, dan ongkos pemilu di DOB baru pun menambah beban APBN.
Maka, kita harus merenung:
Jika pemekaran tidak mendekatkan layanan publik kepada rakyat, untuk apa dilakukan?
Desentralisasi semestinya membangun kemandirian daerah, bukan menambah beban fiskal dan birokrasi tak produktif. Sebelum satu pun usulan DOB baru disetujui, pemerintah pusat wajib menjawab pertanyaan kunci: Apakah rakyat benar-benar akan lebih sejahtera?
Seperti saya sampaikan dalam opini Harian Kompas, 12 Maret 2025:
“Jika ujungnya hanya memperbesar beban anggaran birokrasi, maka itu akan semakin menggerus kapasitas pemerintah untuk berinvestasi dalam sektor produktif yang mendorong pertumbuhan jangka panjang.”
Maka, sebelum wilayah-wilayah kita terus “mekar”, pastikan terlebih dahulu kita telah benar-benar “kekar”. (RH)
Nicholas Martua Siagian Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia Seorang sivitas akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menerima penghargaan dari Pimpinan KPK pada tahun 2021 sebagai Penyuluh Antikorupsi Inspiratif.