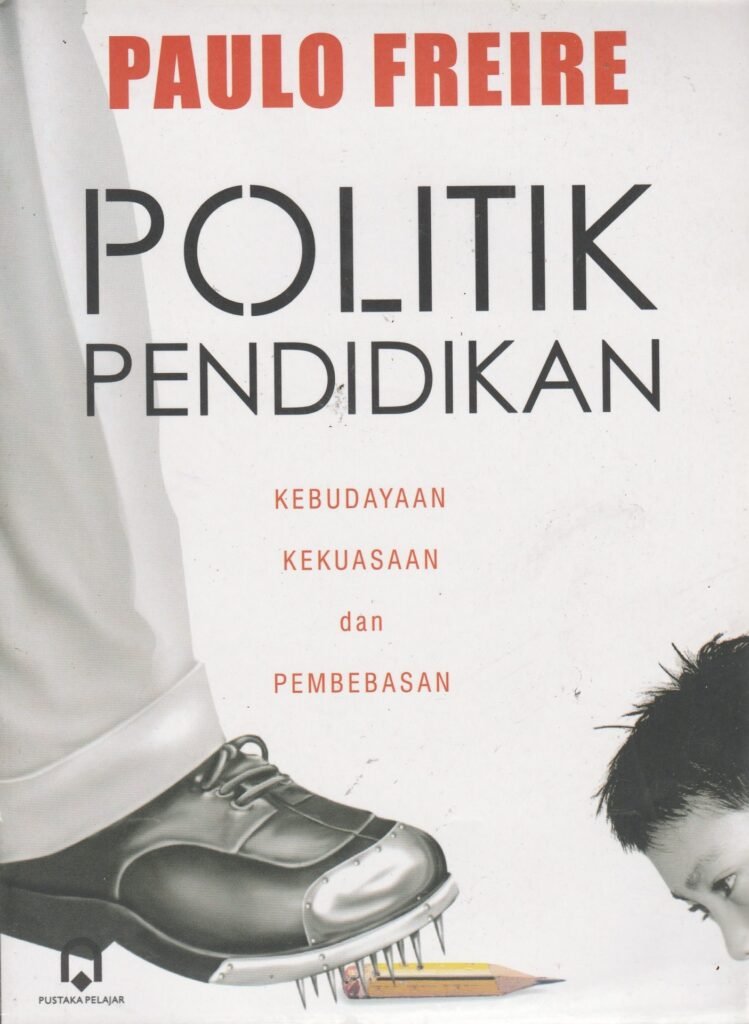PRADANAMEDIA / JAKARTA – Unjuk rasa di depan Gedung DPR-MPR RI, pada 25 Agustus 2025 bukan sekadar demonstrasi biasa. Aksi massa menolak pemberian tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan bagi anggota DPR mencerminkan krisis kepercayaan yang semakin dalam terhadap lembaga legislatif.
Alih-alih membuka ruang dialog, aparat justru memilih langkah represif: membubarkan massa dengan water cannon, gas air mata, dan pentungan—padahal aksi belum melewati batas waktu yang sah menurut undang-undang. Peristiwa ini menegaskan kenyataan pahit: “rumah rakyat” kini semakin tertutup, baik secara fisik maupun simbolik, bagi suara rakyat.

Ketimpangan yang Menyulut Kemarahan
Penolakan publik berakar pada ketidakadilan sosial-ekonomi. Berdasarkan data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), total penghasilan anggota DPR mencapai sekitar Rp 230 juta per bulan—belum termasuk tunjangan tambahan. Angka ini setara 42 kali UMR Jakarta, bahkan lebih dari 100 kali UMR terendah di Indonesia, yakni Banjarnegara.
Di tengah tekanan ekonomi rakyat, jumlah fantastis ini bukan hanya tidak adil, melainkan juga provokatif. Ironisnya, kompleks DPR kini dikelilingi pagar tinggi dan barikade kokoh, seolah menjadi benteng yang memisahkan wakil rakyat dari konstituennya. Pagar itu bukan hanya penghalang fisik, tetapi simbol keterasingan politik.
Demokrasi yang Terkikis
Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari teori demokrasi. Robert A. Dahl (1998) menegaskan bahwa demokrasi hanya hidup jika ruang partisipasi rakyat dibuka. Sementara Peter Mair (2013) memperingatkan tentang “hollowing of democracy”, di mana elite politik semakin menjauh dari rakyat sehingga sistem kehilangan legitimasi.
Kegelisahan itu kini nyata di Indonesia. Dalam aksi 25 Agustus, massa tidak hanya menuntut pembatalan tunjangan, tetapi juga menyerukan pembubaran DPR. Yang hadir bukan hanya mahasiswa, tetapi juga pekerja informal, pedagang kaki lima, hingga pelajar—menandakan gerakan ini tumbuh organik dari rakyat, bukan digerakkan elite oposisi.
Sayangnya, respons negara justru represif. Tindakan membubarkan aksi damai sebelum waktunya melanggar prinsip hak asasi warga sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Bahkan Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra mengakui, usulan pembubaran DPR sekalipun sah-sah saja selama disampaikan secara damai.
Legitimasi yang Runtuh
Tidak ada lembaga demokrasi yang sakral atau kebal kritik, termasuk DPR. Ketika wakil rakyat justru menjadi beban anggaran dan gagal menunjukkan empati pada kesulitan ekonomi, maka seruan pembubaran bukan sekadar agitasi, melainkan peringatan keras.
Argumen bahwa pendapatan tinggi dibutuhkan untuk operasional di daerah pemilihan pun rapuh, karena tidak pernah disertai transparansi data. Tanpa akuntabilitas, alasan itu hanya memperdalam kecurigaan publik.
Jalan Keluar: Membuka Kembali Rumah Rakyat
Demokrasi bukan hanya soal pemilu lima tahunan, tetapi juga soal mendengarkan rakyat di luar masa kampanye. Jika suara rakyat hanya dijawab dengan gas air mata, maka demokrasi kita hanya akan tersisa bentuknya, kosong dari jiwa partisipasi dan keadilan sosial.
Ada tiga langkah mendesak:
- Evaluasi tunjangan DPR yang tidak rasional di tengah krisis ekonomi.
- Membuka kembali akses fisik dan simbolik DPR agar rakyat benar-benar punya ruang menyampaikan aspirasi.
- Instruksi tegas kepada aparat untuk menjamin hak konstitusional rakyat dengan pendekatan persuasif, bukan represif.
Jika langkah-langkah itu diabaikan, maka pagar tinggi DPR akan terus berdiri sebagai metafora krisis: lembaga yang semestinya menjadi representasi rakyat justru menjauh dari rakyatnya. Dan itu artinya, kita sedang melangkah menuju demokrasi kosong—yang hanya ada wujud, tanpa ruh partisipasi. (RH)